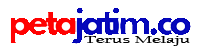Oleh : Rizal Hamduddin A.S (Aktivis Mahasiswa Sampang)
SAYA pernah mendengar Ibu Guru saat Sekolah Dasar dulu menjelaskan Bahwa Kemanusiaan Yang Adil Beradab merupakan Sila Ke-2 Pancasila.
Sila yang menjadi pelengkap dari sila ke-1 yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Setelah mengakui adanya Tuhan yang satu, maka manusia sebagai makhluk Tuhan pun harus diberikan hak dan kewajibannya, harus diperlakukan selayaknya manusia dalam konsepsi “Memanusiakan Manusia”.
Namun apa yang saya temukan, ratusan warga penyintas korban Konflik Sunni Syiah masih terlunta lunta di tempat pengungsian setelah dipulangkan kembali.
Dua belas tahun hidup di tempat pengungsian sangat tidak mereka inginkan. Dua belas tahun mereka memendam impian hidup kembali di kampung seperti dahulu. Hidup tentram dan damai bertetangga.
Bila malam tiba, mereka bisa menikmati secangkir kopi sambil bercanda dengan istri dan anak anak mereka di rumahnya masing-masing.
Sayang, Impian mereka pulang ke kampung halaman dan memiliki rumah hunian menyisakan iming-iming. Janji manis sang mantan Bupati Sampang tak jua terwujud.
Kini,mereka tak tahu hendak kemana mengadukan semua. Waktu sudah berjalan dua tahun lamanya sejak mereka di- upacara kan pulang kembali.
Melihat ini, setelah dua tahun lamanya,hati kecil bertanya, apakah upaya pemulangan kembali hanya ingin memenuhi hasrat sang mantan Bupati yang haus puja puji dalam klaim prestasi. Apakah pemulangan itu hanya ibarat olesan gincu/lipstik sang wanita malam untuk menarik para lelaki hidung belang?
Jika benar, maka selama ini patutlah diduga bahwa para penyintas hanya dijadikan boneka komoditas politik dan popularitas. Lalu dimana konsep “Memanusiakan Manusia nya? “
Entahlah, yang bisa menjawab hanya Tuhan dan sang Mantan Bupati Sampang.
Dulu Ibu Guru juga menerangkan bahwa setelah sila ke-3, “Persatuan Indonesia” yang menjadi pedoman bahwa manusia warga negara ini harus bersatu. Lalu ada sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Di mana artinya, bahwa rakyat dipimpin dalam kebijaksanaan. Harus dikembangkan nilai nilai demokrasi dalam mengelola kekuasaan.
Namun apa yang saya dapatkan di kotaku,Sampang!. Ototarianisme menjelma wajah-wajah baru di tingkat lokal. Intimidasi memenuhi ruang ruang birokrasi. Kebijakan “SATU PINTU” telah mematikan nalar dan daya kreatifitas birokrasi.
Jalannya pemerintahan, berada dalam nuansa ketakutan penuh tekanan. Semua program dan kebijakan dalam settingan BO (by order). Lalu dimana Good Government berada sebagai implementasi sila ke-4?.
Tidak hanya itu, pembungkaman terhadap suara suara kritis kelompok sipil terus dilakukan selama berkuasa. Sehingga nyaris mayoritas ormas dan kelompok-kelompok sipil lainnya tak berani protes dan mengkritisi kebjakan.
Kondisi yang seperti itu pernah dilawan oleh Anis Bawesdan dengan istilah ” Wakanda No More“.
Dulu juga, Saya pernah memperhatikan dengan seksama tatkala Ibu Guru mengurai makna Sila ke-5 ” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Kata Bu Guru kala itu, Implementasi sila ke-5 dalam pembangunan harus menganut prinsip pemerataan. Pembangunan kesejahteraan harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat bukan kepentingan pribadi. Pembangunan harus seimbang baik di desa maupun di kota. Tanpa harus memandang si kaya dan si miskin.
Nyatanya, justru yang saya temui sebuah ironisme pembangunan di Kotaku, Sampang!
Di tengah angka Kemiskinan yang tinggi dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah malah berlomba cari Hutangan untuk Pembangunan Infrastruktur yang tidak dibutuhkan.
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sedikitpun tidak memiliki dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Coba sebutkan potensi ekonomi apa yang tertolong dengan adanya JLS itu? Jawabannya tidak ada!.
Padahal sudah ada Jalan Pangarengan-Torjun yang sudah bagus kalau hanya untuk jalur alternatif. Semestinya di sepanjang jalan Pangarengan-Torjun itulah dikembangkan sentra-sentra industri dan ekonomi baru. Sebab di kawasan itu terkenal dengan potensi Garam dan perikanannya.
Ironisme lainnya, puluhan tahun lamanya warga memimpikan Jembatan Sreseh-Pangarengan (Serpang) terwujud namun dikandaskan oleh Mega proyek JLS yang menelan anggaran hingga ratusan miliar.
Banyak analisis yang mengatakan bahwa jembatan Serpang itu sangat berguna untuk membuka isolasi kawasan, percepatan distribusi garam, pengembangan potensi wisata laut dan perikanan.
Namun, lagi-lagi sang penguasa kala itu ingin gagah-gagahan untuk memamerkan JLS sebagai karya monumental. Padahal tak menjawab kebutuhan rakyat.
Sementara itu, di saat setoran hutang mencapai 50 milyar per tahun, jalan poros di pelosok dan infrastruktur pendukung ekonomi lainya yang menjadi tanggung jawab pemerintah masih banyak tak terbangun dan tak terurus.
Sampai di sini, bolehkan saya bertanya “Hutang Pembangunan JLS itu sebenarnya untuk Siapa?
Satu yang pasti dan jelas akan menjadi beban pembangunan bagi pemerintah selanjutnya. Persis seperti kata pepatah ” Tidak Ikut Makan Nangkanya Kebagian Getahnya”.
Lalu muncul alibi alibi sesat dengan mengatakan “Jokowi saja Berhutang Untuk Membangun”. Apalagi Bupati!
Ketahuilah wahai saudaraku, Presiden Jokowi membangun jalan tol, dermaga, pelabuhan dan bandara itu dengan sistem investasi. Artinya dari situ negara bisa mendapatkan impact atau pemasukan ekonomi yang jelas. Sementara kalau JLS apa?.
Wassalam…